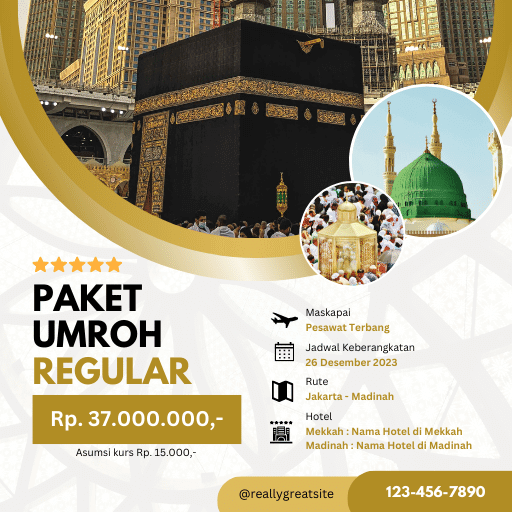Oleh : PROF. DR. H. MIFTAH FARIDL
Ketika penulis buku ini meminta saya memberikan pengantar, secara tidak disengaja saya menemukan tulisan dalam internet, sebuah kisah teladan tentang seorang anak yang tak tahan menghadapi musibah. Seorang ibu memberikan pelajaran tauhid kepada anak kandungnya yang hampir prustrasi itu.
Suatu ketika, seorang anak memberitahu ibunya kalau segala sesuatu tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Dia mendapatkan nilai jelek di sekolah, pinsil kesayangannya hilang, dan sahabat terbaiknya pindah ke luar kota.
Saat itu kebetulan ibunya sedang membuat kue, dan menawarkan apakah anaknya mau mencicipinya.
Dengan senang hati anak itu berkata, “Tentu saja, I love your cake.”
“Nih, cicipi mentega ini”, kata ibunya menawarkan. “Yaiks”, ujar anaknya.
“Bagaimana dengan telur mentah?”
“You are kidding me, Mom.”
“Mau coba tepung terigu atau baking soda?”
“Mom, semua itu menjijikkan.”
Lalu ibunya menjawab, “Ya, semua itu memang kelihatannya tidak enak jika dilihat satu per satu. Tapi jika dicampur jadi satu melalui satu proses yang benar, akan menjadi kue yang enak.”
Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Seringkali kita bertanya, kenapa Dia membiarkan kita melalui masa-masa yang sulit dan tidak menyenangkan. Tapi Tuhan tahu jika Dia membiarkan semuanya terjadi satu per satu sesuai dengan rancangan-Nya, segala sesuatunya akan menjadi sempurna tepat pada waktunya. Kita hanya perlu percaya proses ini diperlukan untuk menyempurnakan hidup kita.
Tuhan teramat sangat mencintai kita. Dia mengirimkan bunga setiap musim hujan, sinar matahari setiap pagi. Setiap saat kita ingin bicara, Dia akan mendengarkan. Dia ada setiap saat kita membutuhkan-Nya, Dia ada di setiap tempat, dan Dia memilih untuk berdiam di hati kita.
***
Ketika banjir menyerbu ibu kota, gempa menghujat Yogyakarta, angin beliung menerpa sejumlah daerah di tanah air, rasa khawatir lalu menyelimuti hampir semua penduduk negeri. Sepucuk surat ditemukan seorang ibu.
“Tadi malam, Jakarta tenggelam”, ujar penulis surat itu dalam secarik kertas setengah basah. Tak kuasa menahan haru, sambil meneteskan air matanya yang hampir kering, ibu memandang jauh anak-anaknya yang tengah menjerit terhimpit berbagai bencana yang akhir-akhir ini menimpa jasadnya yang semakin tua. Bertubi-tubi bencana itu menimpa dirinya, hingga lelah merasakan betapa maut kini menjadi teman akrab bermain anak-anak bangsa yang telah lama diterpa berbagai krisis.
Ibu itu adalah ibu pertiwi. Dia menangis karena tak mampu lagi menahan derita. ” Ada apa sebetulnya di balik semua ini”, tanya ibu pada dirinya sendiri. “Apakah karena kehendak alam atau merupakan jawaban atas berbagai kekeliruan?” lanjutnya sambil menatap di sana sini ada bencana. Lalu ia membuka mata sambil melakukan refleksi sederhan.
”Mungkin karena anak-anak sendiri telah lupa akan amanah yang diberikan kepada mereka. Mereka seharusnya memelihara untuk tujuan kesejahteraan manusia, tapi mereka menyia-nyiakannya dengan cara menguasai seolah kekayaan itu milik sendiri. Atau karena kehendak Tuhyan di mana bencana selalu terjadi pada setiap generasi. Bukankah banjir juga pernah terjadi pada zaman Nuh ’alaihissalam.”
Ibu tidak bisa menjawab ketika anak-anak bertanya. Ibu juga tak berdaya, ketika anak-anak itu merusak bagian tubuhnya yang kini semakin kotor terkena polusi. Lihatlah, Sidoarjo makin sembunyi tertutup lumpur. Anak-anak kandungnya harus rela meninggalkan tanah leluhur tempat kelahirannya. Mereka dibekali ganti rugi, meski harus kehilangan suasana sosial yang telah lama tumbuh bersama perjalanan hidupnya dari waktu ke waktu. Anak-anak ibu juga ketakutan di Yogyakarta. Masih terngiang jerit tangis ketakutan di Aceh dan Sumatra Utara, di Pangandaran dan di beberapa tempat lainnya anak-anak terbirit-birit dikejar ancaman bencana alam. Dan, hanya terjadi di sini di dunia ini, ada sampah yang tega merenggut nyawa manusia.
Kini, anak-anak itu menangis karena tak kuasa menahan sakit. Mereka hancur diterkam goncangan tsunami, porak poranda dimakan gempa bumi, lari dikejar banjir lumpur yang sebelumnya tidak pernah terjadi, ditambah lagi ancaman berbagai penyakit yang samakin menakutkan. Para peternak harus rela kehilangan unggas karena dimusnahkan untuk menghindari virus flu burung. Ibu pun menangis tak kuasa menahan pilu kehilangan anaknya yang terserang demam berdarah. Harga sembako melambung tinggi, BBM semakin lari meninggalkan kemampuan daya beli, sementara lahan pekerjaan semakin sempit menutup peluang penghasilan. Seolah tidak ada ujungnya musibah ini menimpa ibu pertiwi.
Belum lama berselang, dari udara, pesawat jatuh membawa korban ratusan jiwa manusia; dan di laut pun terjadi tragedi yang menenggelamkan anak-anak tak berdosa. Belum kering mata ibu menangis, tiba-tiba terdengar lagi jeritan anak manusia dari arah perjalanan kereta api. Berkali-kali pesawat udara menghadapi bencana, berkali-kali pula kereta api tergelincir atau bahkan bertabrakan. Berita-berita yang mengisi perut ibu pertiwi kerap membuat anak-anak paranoid. Sebentar-sebentar terdengar berita banjir, tidak lama kemudian berita gempa, angin beliung, gunung meletus, kecelakaan transportasi, kelaparan, dan semua hal yang serba menakutkan.
Anehnya, ketika orang-orang sedang ketakutan, masih ada orang-orang yang sama sekali tidak pernah merasa takut. Ketika orang berpikir bahwa bencana ini sesungguhnya adzab dan peringatan Sang Pencipta, mereka malah sibuk mencari pembenaran untuk menghindari kekhilafan. Mereka tidak merasa takut akan adzab Allah, ketika wakil rakyat lebih suka mengurus kenaikan gaji ketimbang memikirkan nasib rakyat. Mereka tidak takut akan murka Allah, ketika kebijakan telah membuat orang-orang yang tengah beribadah di Arafah berteriak kelaparan. Mereka membuat kalkulasi efisiensi, padahal tanpa disadari telah membuat para jamaah di tanah suci terlantar.
Mungkin, inilah petaka ibu pertiwi, ketika alam tidak lagi bersahabat dengan para penghuninya. Kini, kemarahan ibu pertiwi tidak lagi bisa dihalang-halangi. Kesabarannya telah terlalui, dan menangis pun sudah bukan lagi solusi.
Menghadapi kenyataan seperti ini, kita sering pasrah karena tak berdaya. Kadang kita pun bertanya dalam hati, lalu bergumam sambil sesekali menyalahkan Tuhan, “Apa yang telah saya lakukan sampai saya harus mengalami ini semua?” Atau, “Kenapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi pada diri saya?”
***
Tidak sederhana memang membukakan mata dan hati manusia, terutama ketika musibah sedang menimba dirinya. Kadang, orang tabah menerimanya sebagai ujian untuk mempertebal keimanan. Tapi tidak sedikit pula orang yang malah menuduh Tuhan karena telah berbuat khianat pada manusia.
Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Buku ini ingin menyapa para pembacanya untuk tetap bangkit berusaha melawan derita dalam sikap yang sesuai dengan anjuran agama. Buku ini bukan hanya memaparkan arguemen normatif tentang sikap sabar dalam menghadapi musibah, tapi juga sangat kaya dengan ilustrasi empirik dengan mengungkap pengalaman teladan dari sejumlah aktor yang berhasil melawan derita.
Buku ini tentu sangat baik untuk dibaca, terutama untuk menemani kita ketika sedang sendiri tak kuasa menahan derita. Buku ini akan mengajak kita untuk tetap tegar dan tawakkal. Selamat membaca.