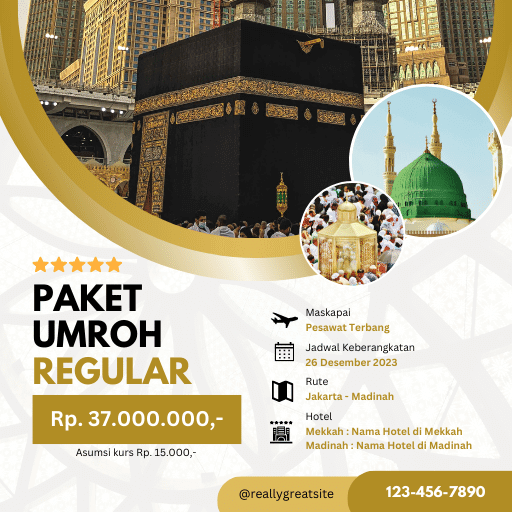OLEH : PROF. DR. H. MIFTAH FARIDL
Dalam sejarahnya, dakwah Islam hampir selalu meniscayakan adanya tantangan. Tantangan itu berubah dari zaman ke zaman seiring perkembangan peradaban umat manusia. Jika mu’jizat merupakan fasilitas para nabi dalam menghadapi tantangan kaum yang dihadapinya, maka nampak jelas perubahan itu pada keragaman bentuk mu’jizat yang dimilikinya. Mengapa, misalnya, Nabi Musa diberi tongkat yang dapat berubah menjadi ular raksasa? Karena Musa saat itu harus berhadapan dengan kaum yang tengah terlibat dalam tradisi sihir. Hanya dengan cara itu mereka dapat ditaklukkan, meskipun pembangkangan sebagian kaum pun selalu saja ada.
Tapi mengapa tongkat sakti itu tidak diberikan kepada Nabi Muhammad? Tidak! Dan mu’jizat terbesar Nabi Muhammad adalah al-Qur’an. Karena Nabi Muhammad saat itu diutus di tengah kaum yang tengah gandrung dengan tradisi sastra. Pasar Ukaz di Makkah, misalnya, adalah di antara pesta tahunan yang menjadi salah satu momentum untuk mempertontonkan kehebatan karya-karya sastra. Maka, al-Qur’an hadir untuk menaklukkan para pesohor sastra saat itu. Gaya bahasa al-Qur’an pun diakui mereka memiliki nilai sastra yang tidak bisa ditandingi siapapun. Seharusnya mereka pun takluk, meski kenyataannya memang tidak sesederhana itu.
Lalu sejarah dakwah itu berjalan menembus zaman-zaman berikutnya. Setiap zaman yang dilaluinya selalu ada tantangan tersendiri. Masuk Mesir, telah tersedia peradaban kuno yang telah berusia ribuan tahun silam dan berakar pada kehidupan masyarakat. Masuk Gujarat, dakwah Islam bertemu dengan tradisi mistisisme yang telah lama dikembangkan Hinduisme dan Budisme. Sulit dihindari adanya akomodasi ritual, sehingga lahirlah mistisisme Islam yang kemudian berkembang dalam corak keagamaan para sufi.
Gilirannya Islam masuk ke Nusantara. Dakwah pun berhadapan dengan masyarakat yang telah lama dimanjakan para pendahulunya dengan beragam tradisi yang sulit dipisahkan dari kehidupannya. Tapi bukan berarti harus menyerah. Ketika Islam masuk ke daratan Nusantara pada sekitar Abad ke-13, dakwah pun berlangsung melalui saluran-saluran yang paling mungkin dapat melakukan kompromi-kompromi kebudayaan. Sebab Nusantara saat itu bukanlah kawasan yang hampa kebudayaan, tetapi merupakan rumah suatu kaum yang telah berperadaban. Masyarakatnya telah berusia cukup lama, sehingga otomatis telah menjadi sosok yang sarat dengan tradisi serta nilai-nilai yang sebelumnya telah lebih dulu mewarnai kehidupan.
Proses islamisasi yang dilakukan oleh para wali pun berlangsung melalui pendekatan-pendekatan kultural yang paling mudah diterima. Dipertemukanlah tradisi-tradisi setempat dengan nilai-nilai ajaran selama proses yang dilaluinya tidak mengganggu prinsip aqidah yang menjadi pokok ajaran Islam. Sehingga dengan pendekatan-pendekatan dakwah seperti inilah Islam dapat memasuki ruang-ruang kehidupan masyarakat Nusantara, dan dalam tempo yang tidak terlalu lama Islam pun menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Nusantara.
Sejarah memperlihatkan sebuah drama kebudayaan dalam wujud yang beraneka ragam. Masuknya nilai-nilai agama pada kebudayaan Wayang Golek di tatar Sunda, misalnya, atau pada upacara “Sekatenan” pada pusat-pusat kekuasaan raja-raja pada zaman itu, memberikan inspirasi positif bagi proses adaptasi Islam dalam konteks kebudayaan setempat. Seolah-olah kenyataan ini merupakan pilihan yang paling mungkin dilakukan agara Islam sebagai agama “baru” dapat mudah diterima. Sebab hadirnya kepercayaan-kepercayaan lain yang telah mapan menjadi agama pribumi sebelum Islam datang, merupakan kenyataan yang sama sekali tidak bisa dinafikan. Maka jadilah Islam Indonesia seperti yang saat ini kita saksikan.
Kini, di era cyberspace yang sarat dengan tantangan etik maupun sosial, tantangannya pun terus berubah. Berkaitan dengan ikhtiar mengoptimalkan peran gerakan dakwah, sekurang-kurangnya ada tiga agenda permasalahan penting, yaitu (1) berkaitan dengan pola-pola pengembangan da’wah yang selama ini dilakukan oleh para juru da’wah, baik secara individual maupun kelembagaan; (2) berkenaan dengan muatan pesan yang disampaikan pada setiap kesempatan da’wah dilakukan; dan (3) berkenaan dengan pentingnya dirumuskan ulang suatu pendekatan alternatif dalam memperkenalkan Islam secara komprehensif persuasif di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam konteks inilah, saya kira, buku Save Maryam: Ketika Kejujuran Gugur Atas Nama Dakwah karya Maulana M. Syuhada ini menjadi penting dihadirkan. Secara substansi, buku ini menggariskan proses mujādalah bi allatī hiya ahsan. Sedangkan dilihat dari sisi media yang menjadi saluran utamanya, buku ini menjadi potret sederhana dakwah di era yang penuh tantangan teknologi informasi ini. Melalui rekayasa teknologi, suatu kebohongan dapat dikemas sehingga nampak tersaji sebagai sebuah kebenaran. Tidak mudah dideteksi memang, kecuali oleh orang-orang yang memiliki referensi yang kuat sehingga kebathilan itu tetap terlihat sebagai kebathilan.
Jadi, selain isinya yang memang penting untuk diketahui, buku ini juga sekaligus mengingatkan kita untuk memiliki agenda dakwah yang lebih terorganisasi dengan baik. Perlunya dirumuskan agenda baru dakwah Islam ini terutama berkaitan dengan ikhtiar antisipatif atas berbagai kekhawatiran dampak negatif perkembangan media interaktif yang semakin jauh memasuki hampir seluruh pojok kehidupan masyarakat. Benar bahwa media interaktif semacam internet telah memungkinkan para penggunanya lebih dapat melakukan kontrol interaksi mereka dengan menginterpretasikan material yang mereka terima, sebagaimana pula mereka mengkonstruksi pesan-pesan dalam media. Masyarakat sasaran dakwah pun akan semakin kreatif dan melek media dalam cara mereka berkomunikasi dengan sesamanya, meski tidak selalu dapat menghindari resiko yang muncul dari adopsi teknologi semacam ini.
Peran dakwah sebagai penjamin tetap hidupnya nilai-nilai orisinal agama kemudian dipertaruhkan. Eksistensi dakwah sendiri, di samping befungsi sebagai saluran kulturalisasi ajaran dalam tataran kehidupan masyarakat, secara makro, juga senantiasa bersentuhan dan bergumul dengan tuntutan dinamika masyarakat yang mengitarinya. Pada tahap tertentu, pergumulan Islam-kebudayaan itu dapat saja melahirkan tuntunan baru berkenaan dengan proses pembentukan pranata-pranata kehidupan lainnya, seperti pranata sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Di sinilah dakwah dapat dilihat sebagai suatu proses yang dinamis, atau suatu kekuatan yang hidup dalam mobilitas sosial tertentu, dan yang pada gilirannya merupakan daya pendorong terbentuknya sistem sosial di mana dakwah itu dilaksanakan.
Seperti dipaparkan penulisnya, buku ini bermula dari ikhtiar merespon sekaligus mengklarifikasi penyebaran informasi yang dirancang oleh suatu institusi yang menamakan diri Save Maryam, suatu gerakan yang diduga kuat secara sengaja bertujuan merusak citra Islam. Lembaga ini telah melakukan gerakan tertentu dengan mengatasnamakan dakwah. Padahal, gerakan yang dilakukannya sangat bertolak belakang, dan bahkan dapat memancing konflik antarumat beragama. Untuk kepentingan meluruskan gerakan Save Maryam ini, penulis buku ini telah membuka diskusi serta dialog-dialog yang lebih luas.
Jadi, sebagai bahan renungan sekaligus ikhtiar mengantisipasi munculnya berbagai gerakan yang dapat membahayakan dakwah, buku ini sangat baik untuk dimiliki (dan tentu untuk ditelaah), khususnya para juru dakwah. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada penulisnya atas usaha yang sangat produktif ini.