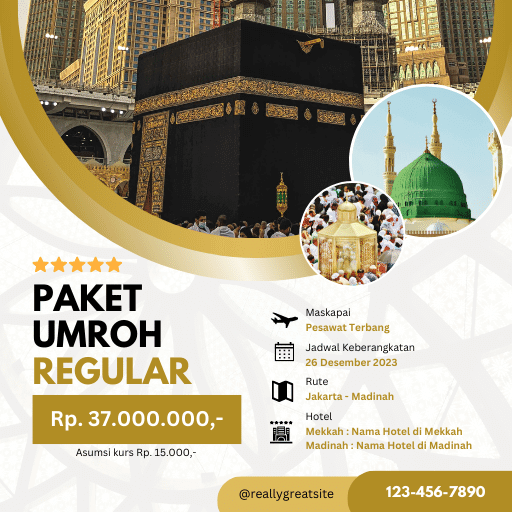Oleh : Prof. Dr. Miftah Faridl
Beberapa waktu yang lalu, saya meluncurkan buku Rumahku Surgaku (2005). Secara substansial, buku itu merupakan rekaman sederhana tentang berbagai masalah keluarga yang ditemukan dari berbagai pengungkapan kegelisahan sejumlah istri dan/atau suami dari berbagai lapisan keluarga. Menurut beberapa pembaca, buku ini lahir tepat waktu. Ia hadir di tengah arus pergeseran nilai sosial dalam masyarakat yang tampak cenderung semakin permisif khususnya dalam masalah keluarga. Keluarga tidak lagi dilihat sebagai ikatan spiritual yang menjadi ruang pengabdian kepada Sang Pencipta. Kawin-cerai cenderung dilihat sebatas proses formal sebagai simbol ikatan sosial antara dua insan yang berbeda jenis. Perkawinan juga tidak lagi dilihat sebagai proses sakral yang menjadi bagian dari rahasiah Allah.
Padahal, di sisi lain, banyak asumsi yang menyatakan bahwa keluarga merupakan sentral masalah dalam membangun masa depan bangsa. Dari rahim keluarga lah lahir berbagai gagasan perubahan dalam menata tatanan masyarakat yang lebih baik. Tidak ada satu bangsa pun yang maju dalam kondisi sosial keluarga yang kering spiritual, atau bahkan sama sekali sudah tidak lagi mengindahkan makna religiusitas dalam hidupnya. Karena itu, al-Qur’an memuat ajaran tentang keluarga, mulai dari urusan komunikasi antar individu dalam keluarga, hingga relasi sosial antar keluarga dalam masyarakat.
Banyak memang problema yang biasa dihadapi keluarga. Banyak keluarga yang tidak lagi sanggup menahan “derita” yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Tidak sedikit pula di antaranya yang memilih perceraian, padahal pilihan itu sangat dibenci Allah meskipun hukumnya halal. Sekedar ilustrasi, dalam tulisan sederhana ini, saya ingin mengungkap beberapa kasus menarik dan faktual yang pernah dialami sebagian masyarakat kita.
Ilustrasi Sederhana
Seorang ibu setengah tua ditemani gadis usia tiga puluh tahunan yang kemudian diketahui adalah putrinya sendiri, suatu waktu datang menemui saya. Keduanya menunggu giliran konsultasi di antara jamaah lainnya yang telah terbiasa berkonsultasi. Perilakunya mencerminkan seseorang yang sedang gelisah menghadapi beban pikiran yang sulit diselesaikan sendiri. Ketika giliran tiba, ibu itu pun bergegas seolah ingin segera menumpahkan beban pikirannya yang beberapa minggu terakhir dirasakannya sangat berat.
“Pak Miftah”, ibu itu memulai perbincangannya penuh perhatian, “anak saya ini mau dilamar seseorang. Tapi yang melamarnya seorang perempuan yang telah dikaruniai tiga orang anak. Dia mau melamar anak saya untuk istri kedua suaminya.” Ibu itu menatap penuh harap. “Pak Miftah”, lanjutnya lagi, “bagaimana jika kelak benar-benar terjadi?”
Ini memang peristiwa langka. Seorang istri mencarikan calon istri kedua untuk suaminya sendiri. “Tapi ia nampak tulus”, papar ibu itu menjelaskan. Bukan karena marah pada suami, tapi justeru sebaliknya, ia mencoba memahami laki-laki yang sebetulnya adalah suaminya sendiri. Ia tengah berusaha mengerti akan kebutuhan umumnya laki-laki. Meski kenyataan ini tergolong langka, tapi inilah yang saat itu terungkap jujur.
Pada hari yang berbeda, datang pula seorang ibu untuk menemui dan meminta pendapat saya. Ia membuka masalah yang tengah dihadapinya pada beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangganya. Awalnya masih setengah ragu ibu itu mengungkapkan perasaan yang semakin menghimpit napasnya setiap hari. Meski akhirnya ibu itu pun terbuka lebar. “Ustadz”, begitu dia memanggil saya agak pelan. “Saya ingin menjadi istri yang solihah, paling tidak buat suami saya.” Lalu ia terdiam sejenak, sebelum melanjutkan pada inti masalah yang tampak dibawanya begitu berat.
“Saya tahu kalau suami saya punya istri lagi”, lanjutnya sambil menarik napas panjang. “Tapi selama ini saya berusaha pura-pura tidak tahu. Saya juga setuju kalau suami saya beristri lagi. Saya tulus, ikhlas. Toh dia telah memilih jalan yang benar. Dari pada selingkuh melalui jalur yang tidak syah. Suami saya juga tidak pernah mengurangi perhatian dan nafkah pada saya. Bahkan setiap malam ia selalu berada bersama saya dan anak-anak saya.”
“Lalu kenapa?”, tanya saya sambil memulai memberikan beberapa nasihat tentang bagaimana istri-istri Nabi memperlakukan Nabi sebagai suami mereka. Saya memang hampir selalu mengajak untuk membuka cakrawala pemikiran siapa pun yang datang mengadukan masalah. Saya biasanya bukan hanya memberi, tapi juga mengungkap potensi kemampuan dan pengetahuan yang sebetulnya dimiliki sendiri oleh para penanya.
“Belakangan saya merasa berdosa”, lanjutnya lagi sambil pelan-pelan memotong penjelasan saya yang mulai memasuki inti persoalan yang dibawanya. “Saya merasa berdosa, karena saya telah membiarkan suami saya untuk berbuat tidak adil. Menurut saya, dia telah berbuat dzalim pada istri keduanya. Dia hanya sebentar saja bersama istri mudanya, dan itu pun hanya siang hari di sela-sela kesibukan pekerjaan yang dihadapinya. Sementara di rumah saya, ia tetap hadir setiap malam kecuali jika ada tugas luar kota lebih dari satu hari”. Agak panjang ibu itu menarik napas. Lalu bertanya, sekaligus menutup pembicaraannya sambil menanti jawaban saya: “Jadi, apakah saya ini berdosa?”
Menghadapi persoalan seperti ini, saya biasanya mulai memberikan nasihat sesuai bimbingan ajaran. Seperti biasa dalam menjawab masalah-masalah rumit seperti itu, saya sering merujuk pada kisah orang-orang shaleh, kisah Nabi dan para shahabatnya, kisah istri-istri Nabi beserta keluarganya. Dan, setelah agak lama berdiskusi, kedua tamu itu pun pulang. Tampak ada perubahan sinar mata pada keduanya. Lebih optimistik.
Ini baru dua kasus. Masih banyak kasus menarik lainnya. Banyak di antara kegelisahan yang melilit para tamu itu sama sekali di luar dugaan sebelumnya. Bahkan ada yang betul-betul baru dan mengagetkan. Termasuk kedatangan seorang ibu-ibu yang tanpa ragu meminta jodoh yang tak juga kunjung datang. Banyak yang sangat sulit saya jelaskan. Ada sebagiannya yang saya jelaskan bahwa setiap orang hampir pasti menghadapi masalahnya masing-masing. Kegelisahan umumnya diakibatkan oleh menurunnya kemampuan menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendakinya.
Mengapa Harus Sakinah
Istilah “sakinah” digunakan al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga, seperti menjadi idaman semua orang. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (mawaddah dan rahmah) di antara sesama anggotanya.
Saya ingin menyebut dua tempat dalam al-Qur’an yang mengungkap kata “sakinah”. Pertama dalam surah al-Baqarah, ayat 248. Jika diterjemahkan secara agak bebas, ayat itu berbunyi:
Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat.”
Kata tabut seperti disebutkan di atas, menurut para mufassir, ialah peti tempat menyimpan Taurat yang membawa ketenangan bagi mereka. Seperti disebutkan dalam konteks ayat ini, di dalam peti tersebut terdapat ketenangan, yang dalam bahasa al-Qur’ann disebut sakinah. Dengan kata lain, sakinah adalah tempat yang tenang, nyaman, aman, kondusif bagi penyimpanan sesuatu, termasuk tempat tinggal yang tenang bagi manusia.
Kedua, dengan penambahan alif-lam di awal kata itu, al-sakinah, disebutkan dalam surah al-Fath, ayat 4. “Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mu’min supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada)”.
Dalam ayat yang terakhir ini, kata sakinah diterjemahkan sebagai ketenangan yang sengaja Allah turunkan ke dalam hati orang-orang mu’min. Ketenangan ini merupakan suasana psikologis yang melekat pada setiap individu yang mampu melakukannya. Ketenangan adalah suasana batin yang hanya bisa diciptakan sendiri. Tidak ada jaminan orang lain untuk dapat menciptakan suasana tenang bagi seseorang yang lainnya.
Jadi, kata “sakinah” yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” seperti biasa disebut “keluarga sakinah” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Inilah yang dalam perspektif sosiologis disebut unit terkecil dari suatu masyarakat.
Karena itu, dengan menggunakan cara pandang seperti ini, kasus-kasus yang akhir-akhir ini banyak melilit kehidupan keluarga, di antaranya dapat diduga karena rumah sudah tidak lagi nyaman untuk dijadikan tempat kembali. Suami tidak lagi menemukan suasana nyaman dalam rumah, demikian pula istri. Bahkan anak-anak pun sangat mungkin lebih mudah menemukan suasana nyaman di luar rumah ketimbang di rumah sendiri. Sakinah adalah konsep keluarga yang dapat memberikan kenyamanan psikologis, meskipun mungkin secara fisik tampak jauh di bawah standar nyaman.
Memelihara Kenyamanan Keluarga
Kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama. Melalui proses panjang untuk saling menemukan kekurangan dan kelebihan masing-masing, setiap anggota keluarga akan menemukan ruang kehidupan yang mungkin sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Itulah sebabnya, keluarga pada dasarnya adalah proses pembelajaran untuk menemukan formula yang lebih tepat bagi kedua belah pihak, baik suami-istri, maupun anak-orangtua.
Proses belajar itu akan mengungkap berbagai misteri keluarga. Lebih-lebih ketika kita akan belajar tentang baik-buruk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tidak banyak buku dan teori yang tepat menembak sasaran ketika diperlukan solusi atas problema keluarga. Ilmu membina keluarga lebih banyak diperoleh dari pengalaman. Itulah sebabnya, dalam nasihat-nasihat perkawinan, keluarga sering diilustrasikan sebagai perahu yang berlayar melawan badai samudra. Kita dapat belajar dari pengalaman siapa pun. Pengalaman pribadi untuk tidak mengulangi kegagalan, atau juga pengalaman orang lain selama tidak merugikan pelaku pengalaman itu.
Kasus demi kasus yang dilalui dalam perjalanan sejak pertamakali menikah adalah pelajaran berharga. Kita dapat belajar dari pengalaman orang tentang memilih pasangan ideal, menelusuri kewajiban-kewajiban yang mengikat suami-istri, atau tentang penyelesaian masalah yang biasa dihadapi keluarga. Semuanya sulit kita temukan dalam buku-buku ilmiah sekalipun. Ia ada pada buku raksasa yang disebut kehidupan. Bagaimana kita dapat memahami istri yang biasa buka rahasia, atau menghadapi suami yang berkemampuan seksual rendah. Dan masih banyak lagi masalah keluarga yang seringkali sulit ditemukan jalan penyelesaiannya. Benar, rumah tangga itu ibarat perahu yang tak henti-hentinya menghadapi badai di tengah samudra luas.
Bila dibuat ibarat, rumah tangga adalah dua sisi dari keping uang yang sama. Ia bisa menjadi tambang derita yang menyengsarakan, sekaligus menjadi taman surga yang mencerahkan. Kedua sisi itu rapat berhimpitan satu sama lain. Sisi yang satu datang pada waktu tertentu, sedang sisi lainnya datang menyusul kemudian. Yang satu membawa petaka, yang lainnya mengajak tertawa. Tentu saja, siapa pun berharap, bahwa rumah tangga yang dijalani adalah rumah tangga yang memancarkan pantulan cinta kasih dari setiap sudutnya. Rumah tangga yang benar-benar menghadirkan atmosfir surga: keindahan, kedamaian, dan keagungan, adalah rumah tangga seorang nakhoda yang pandai menyiasati perubahan.
Rumah menjadi panggung yang menyenangkan untuk sebuah pentas cinta kasih yang diperankan oleh setiap penghuninya. Rumah juga menjadi tempat sentral kembalinya setiap anggota keluarga setelah melalui pengembaraan panjang di tempat mengadu nasibnya masing-masing. Hanya ada satu tempat kembali, baik bagi anak, ibu, maupun bapak, yaitu rumah yang mereka rasakan sebagai surga. Bayangkan, setiap hari jatuh cinta. Anak selalu merindukan orang tua, demikian pula sebaliknya. Betapa indahnya itu taman rumah tangga. Sebab yang ada hanya cinta dan kebaikan. Kebaikan inilah yang sejatinya menjadi pakaian sehari-hari keluarga. Dengan pakaian ini pula rumah tangga akan melaju menempuh badai sebesar apapun. Betapa indahnya kehidupan ketika ia hanya berwajah kebaikan. Betapa bahagianya keluarga ketika ia hanya berwajah kebahagiaan.
Tetapi, kehidupan rumah tangga acapkali menghadirkan hal yang sebaliknya. Bukan kebaikan yang datang berkunjung, melainkan malapetaka yang kerap merundung. Suami menjadi bahan gunjingan istri, demikian pula sebaliknya. Anak tidak lagi merindukan orang tua, dan orang tua pun tidak lagi peduli akan masa depan anaknya. Bila sudah demikian halnya, maka bukan surga lagi yang datang, melainkan neraka yang siap untuk menikam. Benar, seperti dikatakan Kahlil Gibran, bahwa orang tua tidak punya hak membesarkan jiwa anak-anaknya, dan mereka hanya boleh membesarkan raganya. Tapi raga adalah cermin keharmonisan komunikasi yang akan berpengaruh pada masa depan jiwa dan kepribadian mereka.
Menggapai Keluarga Sakinah
Membangun derajat sakinah dalam keluarga, memang tidak semudah apa yang kita ceritakan. Ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Beberapa kasus berikut adalah di antara pelajaran yang pernah saya temukan, dan dapat menjadi pelajaran penting untuk mewujudkan indahnya keluarga yang mungkin pernah dimimpikan.
Suatu ketika, seorang ibu datang ke tempat biasa saya menerima para tamu yang sengaja ingin berkonsultasi. Setelah duduk, ibu itu pun membuka bicara. Tapi hanya beberapa penggal kata dia lewati. Selebihnya dia hanya bisa menangis. “Suami saya akhir-akhir ini jarang pulang, Pak”, paparnya singkat. Ia seolah ingin saya mengerti, tanpa harus lebih panjang berbicara. Saya berusaha mengerti. Tidak sulit menangkap maksud utamanya memang. Sebab ibu ini bukan yang pertama mengucapkan penggalan kalimat itu. Sebelumnya, banyak ibu-ibu muda yang bernasib hampir sama, atau bahkan persis sama.
Dari penggalan kalimat yang terungkap dalam kasus di atas, kita juga bisa membayangkan, masalah apa sebetulnya yang sedang dihadapi ibu itu sehingga harus datang untuk membicarakannya pada orang lain. Ini memang bukan satu-satunya masalah yang banyak dikeluhkan pasangan suami-istri. Masih banyak. Tapi kalau dicoba ditelusuri akar masalahnya, umumnya hampir sama. Kata kuncinya hampir sama: “tidak tahan menghadapi godaan”. Sebab godaan itu bisa datang kepada siapa pun. Godaan bisa merapat pada suami, bisa juga akrab dengan istri. Karena godaan itu pula, siapa pun bisa membuat seribu satu alasan. Ada yang mengatakannya sudah tidak harmonis, tidak bisa saling memahami, tidak juga mendapat keturunan, atau ada pula yang karena “intervensi” keluarga yang berlebihan.
Inilah gambaran masalah yang sering saya terima dari banyak pasangan keluarga. Sejak kurang lebih sepuluh tahun terakhir, saya memang banyak mendapat pertanyaan umat di seputar membina keluarga sakinah. Dalam usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat itulah, saya sering terlibat dalam diskusi-diskusi panjang dan menarik. Kasus yang menjadi bahan diskusi itu sangat bervariasi. Mulai dari urusan problem memilih jodoh, kesulitan mendapat pasangan ideal, hingga masalah keberatan seorang istri untuk dimadu oleh suami. Bahkan, yang tidak kalah menariknya, ada juga seorang istri yang mengeluh karena merasa berdosa membiarkan suaminya telah berbuat tidak adil. Dia tahu kalau suaminya beristri lagi. Dia pun tulus mengizinkan suaminya beristri lagi, dari pada berbuat selingkuh penuh dosa. Tapi dia tetap bertahan pura-pura tidak tahu. Dia tidak ingin suaminya merasa malu karena diketahui beristri lagi tanpa memberi tahu istri tuanya. Dan dia mulai gelisah merasa berdosa, karena membiarkan suaminya lebih banyak tinggal bersamanya, dan tidak banyak bersama istri mudanya. Seorang istri itu datang untuk menanyakan hukumnya berpura-pura dan membiarkan suaminya berbuat tidak adil.
Lain orang lain pula masalah yang menghimpit kehidupan keluarganya. Hampir tidak ada hari tanpa “pasien” yang datang membawa masalah. Hingga tanpa terasa, masalah-masalah itu semakin hari semakin bertumpuk. Masalah-masalah itu pula yang kemudian telah mendorong saya untuk terus menggali solusi, merenung menafakuri kenyataan masyarakat yang kian jauh dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Dalam beberapa perenungan lepas setelah para “pasien” itu meninggalkan ruang konsultasi, saya menemukan kegelisahan betapa problema keluarga itu telah menjerat masyarakat semakin tak berdaya. Ada yang karena salah persepsi sehingga mereka pada dasarnya telah tersiksa oleh cara pandangnya sendiri. Ada juga yang karena faktanya memang sangat menyakitkan. Tidak bisa dihindari jika sewaktu-waktu seorang anak tega membiarkan kerinduan ibunya karena ketidakpuasan psikologis ketika ibunya terlalu mempercayakan pola asuhnya hanya pada seorang pembantu rumah tangga.
Dari beberapa kasus yang pernah terungkap, saya pun memperoleh pelajaran berharga, betapa perubahan sosial ini telah menggiring keluarga pada jurang ketidakpastian pegangan. Seorang ibu kehilangan kepercayaan anak dan suaminya. Demikian pula seorang bapak yang tidak lagi berwibawa di hadapan anak dan istrinya. Semua terjadi bukan tanpa argumentasi. Anak yang tidak mau ketinggalan komunitas sebayanya (peer-group), bapak yang tidak mau kalah wibawa istrinya, serta istri yang tidak berhenti memperjuangkan hak-hak kesetaraannya atas suami. Seolah tidak ada yang salah dengan semua kenyataan yang semakin memprihatinkan itu.
Tapi benarkah bahwa perubahan zaman ini merupakan penyebab utama terjadinya pergeseran nilai dalam rumah tangga? Bukankah hukum sosial itu pada dasarnya lahir dari kepentingan kemanusiaan suatu masyarakat? Lalu, mengapa kemudian masyarakat tidak lagi sanggup bertahan dalam norma-norma yang telah kuat mengikat setiap anggotanya untuk tetap bertahan pada jati dirinya yang asli? Seperti halnya para pendahulu dan orang tua mereka yang telah terbukti berhasil mengantarkan mereka menjadi manusia normal dan berbudaya, tanpa harus larut dalam perubahan zaman yang kadang membingungkan.
Transformasi budaya yang berlangsung melalui pertukaran informasi dan komunikasi lewat media, memang bukan sesuatu yang mudah dihindari. Hampir setiap sajian yang sering memperlihatkan perbedaan budaya, kini telah menjadi standar nilai masyarakat kita. Ukuran baik-buruk tidak lagi bersumber pada moralitas universal yang berlandaskan agama, tapi lebih banyak ditentukan oleh nilai-nilai artifisial yang dibentuk untuk tujuan pragmatis dan bahkan hedonis. Tanpa disadari, nilai-nilai itu kini telah membentuk perilaku sosial dan menjadi anutan keluarga dan masyarakat kita. Banyak di antara pertanyaan dan keluhan umat yang berkaitan dengan problema keluarga umumnya menggambarkan kegelisahan yang diwarnai oleh semakin lunturnya nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Masyarakat kini seolah telah berubah menjadi “masyarakat baru” yang pada gilirannya telah membawa suasana yang semakin kabur.
Gaya hidup remaja yang berujung pada pernikahan darurat seolah telah menjadi model terbaru yang digemari banyak pasangan. Pernikahan yang dianjurkan Nabi menjadi jalan terakhir setelah menemukan jalan buntu. Sementara perceraian yang dibenci Nabi justeru menjadi pilihan yang banyak ditempuh untuk menemukan solusi singkat. Kenyataan ini, menurut saya, merupakan bagian kecil dari proses modernisasi kehidupan yang berlangsung tanpa kendali etika. Akibatnya, struktur fungsi yang sejatinya diperankan oleh masing-masing anggota keluarga tampak semakin kabur.
Seorang anak kehilangan pegangan. Ibu-bapaknya terlalu sibuk untuk sekedar menyapa anak-anaknya. Anak itu semakin dewasa. Kini dia harus menemukan jalan hidupnya sendiri. Mencari jalan sendiri kemana dia harus memperoleh pengetahuan, dan bahkan dia harus mendiskusikan sendiri siapa calon pendampingnya. Semuanya berjalan sendiri-sendiri. Padahal, jika sendi-sendi keluarga itu telah kehilangan daya perekatnya dan masing-masing telah menemukan jalan hidupnya yang berbeda-beda, maka bangunan “baiti, jannati”, rumahku adalah surgaku, akan semakin menjauh dari kenyataan. Ia adalah mimpi yang semakin sulit terwujud. Bahkan mungkin mimpi saja tidak pernah terpikirkan. Yang ada hanyalah “neraka” yang tidak henti-hentinya membakar suasana rumah tangga.
Satu lagi yang sering menjadi akar bencana keluarga, yaitu anak. Dunia anak adalah dunia skeptik, dunia yang lebih banyak diwarnai oleh proses pencarian untuk menemukan apa apa yang menurut perasaan dan pikirannya ideal. Dunia ideal sendiri, baginya, adalah dunia yang ada di depan matanya, yang karenanya ia akan melakukan pengejaran atas dasar kehendak pribadi. Akan tetapi, di sisi lain, perkembangan psikologis yang sedang dilaluinya juga masih belum mampu memberikan alternatif secara matang terutama berkaitan dengan standar nilai yang di kehendakinya. Karena itu, selama proses yang dilaluinya, hampir selalu ditemukan berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan tempat di mana anak itu berkembang. Di sinilah proses bimbingan itu diperlukan, terutama dalam ikut menemukan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan.
Guru di sekolah ataupun orang tua di rumah, secara tidak sadar, seringkali menjadi sosok yang begitu dominan dalam menentukan masa depan anak. Padahal, guru ataupun orang tua bukanlah segala-galanya bagi perkembangan dan masa depan anak. Proses pendidikan, dengan demikian, pada dasarnya merupakan proses bimbingan yang memerdekakan sekaligus mencerahkan. Proses seperti itu berlangsung alamiah dalam kehidupan yang retbebas dari ikatan-ikatan yang justru tidak mendidik. Dalam kerangka seperti inilah, maka keluarga bisa berperan sebagai lembaga yang membimbing dan mencerahkan, atau juga sebaliknya, jika tidak tepat memainkan peran yang sesungguhnya, bisa saja berfungsi sebagai penjara yang hanya mampu menanamkan disipliln semu. Anak-anak bisa menjadi manusia yang paling salih di rumah, tetapi menjadi binatang liar ketika keluar dari dinding-dinding rumah dan terbebas dari pengawasan orang tua.
Dalam situasi seperti inilah, anak mulai mencari kesempatan untuk memenuhi kebutuan komunikasi yang dirasakannya semakin kering dan terbatas. Sebab berkomunikasi untuk saling menyambungkan rasa antar anggota keluarga merupakan kebutuhan dasar yang menuntut untuk selalu dipenuhi. Konsekwensinya, ketidaktersediaan aspek ini dalam keluarga dapat berakibat pada munculnya ketidakseimbangan psikologi yang pada gilirannya dapat saja mengakibatkan terjadinya penyipangan-penyimpangan sosial seperti apa yang terjadi pada beberapa kasus di atas. Inilah di antara sumber lunturnya semangat sakinah dalam keluarga.
BAHAN BACAAN
Al-Qur’an al-Karim
Faridl, Miftah. 1986. Keluarga Bahagia: Peraturan Nikah dan Pembinaan Keluarga. Bandung : Pustaka.
——-. 2005. Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga. Jakarta : Gema Insani.
——-. 1999. 150 Masalah Nikah dan Keluarga. Jakarta : Gema Insani.
Rachmat, Jalaludin. 1986. Psikologi Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya.