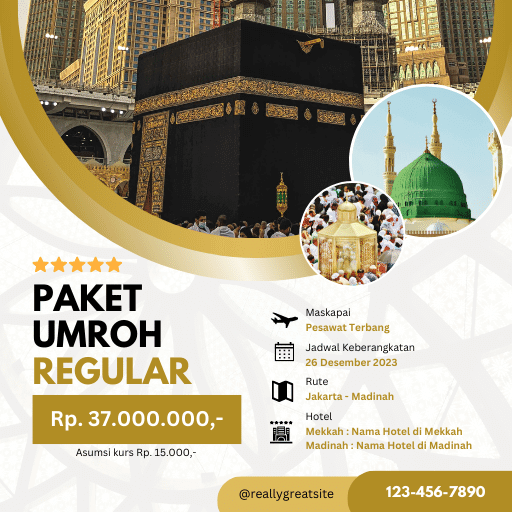Oleh: Prof. Dr. KH. Miftah Faridl
Pada setiap kali Ramadhan, istilah i’tikaf menjadi lebih populer dibandung bulan-bulan lainnya. Seolah-olah kata ini hanya ada pada bulan Ramadhan, dan jika i’tikaf ini merupakan salah satu bentuk ibadah, seolah-olah beribadah i’tikaf hanya bisa dilaksanakan selama bulan Ramadhan. Benar beberapa hadits menyebutkan Nabi SAW beri’tikaf pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan. Hadits yang lain malah menyebutkan sampai dua puluh malam, dan bahkan sepanjang Ramadhan. Tapi benarkan istilah i’tikaf memiliki makna seperti itu?
Tulisan ini tidak bermaksud mengklarifikasi, tapi sekedar memberikan pilihan lain dalam memberikan makna i’tikaf dengan tetap memelihara spirit yang dikandungnya.
Dalam Ensiklopedi Islam (1999), i’tikāf berarti tinggal di dalam masjid yang dilakukan oleh seseorang dengan niat. Dalam sejumlah referensi fiqh yang tersebar dan dibaca di Indonesia, secara istilah, i’tikāf berarti menetap dan tinggal di masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah ‘azza wa jalla. Pengertian ini sama sekali tidak menyiratkan di bulan Ramadhan. Dari sisi waktu, ia netral, yang berarti dapat dilakukan kapan saja, selama tidak ada ketentuan agama yang melarangnya.
Yang secara eksplisit disebutkan dalam pengertian di atas adalah masjid. I’tikaf hanya bisa dilakukan di dalam masjid. Memang ada perbedaan pendapat tentang kategori masjid yang dapat digunakan sebagai tempat i’tikāf. Abu Hanifah, Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur sepakat bahwa i’tikāf hanya dapat dilakukan di masjid-masjid yang biasa dijadikan tempat shalat lima waktu oleh masyarakat umum dan seminggu sekali digunakan untuk shalat jum’at. Nabi SAW sendiri mengisyaratkan “masjid yang mempunyai muadzin dan imam” (HR Daruquthni).
Selama i’tikāf orang dapat melakukan apa saja yang berkaitan dengan proses taqarrub. Ada sebagiannya yang membaca al-Qur’an, berdzikir, atau diisi dengan shalat-shalat sunnat. Lalu pertanyaannya kemudian, dapatkah seseorang yang tengah melakukan i’tikāf melakukan pekerjaan lain dan bahkan dilakukan di luar masjid?
Menurut jumhur ulama, dapat. Ketika Shafiyyah datang menjenguk Rasulullah SAW yang tengah melakukan i’tikāf, ia bangkit untuk meninggalkannya. Lalu Rasulullah pun bangkit dan mengantarkan Shafiyyah pulang. Bahkan dalam beberapa riwayat, dijelaskan bahwa selama i’tikāf seseorang dapat tetap terlibat dalam urusan rumah tangga, seperti mengatur keperluar dapur, menjenguk orang yang sakit, mengantar jenazah dan lain sebagainya. Ia dapat tetap terlibat dalam aktivitas sosial. Ia tidak bisa hanya menjadi dirinya sendiri. Bukankah agama selalu memelihara keseimbangan individu dan sosial?
Jadi setiap perilaku ibadah, termasuk i’tikāf, tidak boleh kehilangan fungsi sosial yang berkaitan dengan dirinya dan juga orang lain. Ibadah ini, dan juga ibadah-ibadah lainnya dalam Islam, selain memberikan pencerahan melalui proses taqarrub kepada Allah, juga harus mampu memberikan dampak produktif bagi kepentingan umum (kemaslahatan sosial). Islam tidak pernah memisahkan secara dikhotomik dua kepentingan tersebut. Bahkan al-Qur’an berkali-kali mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara dua dimensi duniawi dan ukhrawi.
Dengan demikian, jika ajaran i’tikāf masih mencerminkan praktik pengasingan diri secara pasif dengan mengambil posisi di masjid secara penuh selama sekitar sepuluh hari, menarik untuk dikaji ulang, terutama berkaitan dengan kepentingan produktivitas sosial yang juga tidak terlepas dari tuntunan agama. Dalam Islam, tidak mungkin adanya pertentangan antara perintah yang satu dengan yang lainnya. Jika al-Qur’an memerintahkan untuk tetap produktif (‘imalū ‘alā makānatikum), maka seseorang tidak boleh terus menerus duduk dan tidak beranjak untuk mencari dunia.
Proses taqarrub semestinya dapat memberikan semangat produktivitas bagi setiap pribadi yang melakukannya. Seusai taqarrub, seseorang akan menemukan gairah baru untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dan ini tidak cukup hanya ditempuh melalui proses taqarrub pasif, tapi perlu dilengkapi ikhtiar (taqarrub aktif).
Karena itu, dalam Islam, semakin meningkat seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya, semakin produktif dalam kehidupannya. Bukan sebaliknya. Islam tidak pernah menghendaki para pemeluknya lemah dan miskin. Dan pada saat yang sama, Islam juga mengajarkan untuk senantiasa taqarrub kepada Allah. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan secara utuh. Mengejar akhirat seperti akan mati besok, dan memburu dunia seperti akan hidup selamanya.
Reaktualisasi Makna
Untuk menghindari kesalahfahaman dalam praktik i’tikāf, tampaknya perlu dirumuskan makna baru dengan tetap memelihara spirit yang menjadi substansi ajaran itu. Kita tentu tidak bisa memindahkan i’tikāf ke kantor atau ke Supermarket. Bahkan di rumah pun tidak bisa. Secara fisik, i’tikāf tetap hanya dapat dilakukan di masjid. Tapi secara spirit kita harus mampu memelihara i’tikāf di manapun dan kapan pun.
Perubahan (atau bisa juga disebut pembaruan) ajaran seperti ini dimungkinkan dalam Islam. Sejarah perubahan ini telah dimulai sejak periode shahabat, tidak lama setelah Rasulullah wafat. Dalam pelaksanaan shalat tarawih, misalnya, telah terjadi perubahan signifikan bila disbanding dengan tradisi Rasulullah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Argumentasinya jelas, karena Rasulullah saat itu merasa khawatir akan memberatkan umat. Tapi Umar-lah yang pertama kali menginisiasi perubahan itu.
Seperti banyak diungkap dalam sejarah, Umar bin Khattab adalah satu di antara sedikit shahabat yang memiliki keberanian intelektual tersendiri. Kita ingat, misalnya, komentar Umar tentang tradisi mencium hajar aswad di sudut Ka’bah. “Andai saja Nabi tidak melakukan ini, niscaya aku tidak sudi melakukannya”, kata Umar seperti digambarkan dalam salah satu tradisi shahabat (sunnah shahaby). Umar tentu telah berpikir panjang sebelum mengungkapkan buah pikirannya itu. Umar mungkin melihat sisi-sisi yang tidak rasional dari perilaku ibadah yang satu ini. Namun Umar tetap melakukan mencium hajar aswad karena ketulusannya mengikuti apapun yang dicontohkan Nabi.
Selama hidupnya, Umar dikenal banyak berijtihad. Ketika menjadi khalifah, Umar pernah membebaskan seorang pencuri karena alasan yang sangat masuk akal. Pencuri itu diketahui seorang miskin yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Padahal, sebagai sosok pemimpin yang selalu berusaha konsisten dengan hukum, Umar dikenal tegas memberi sanksi kepada siapa pun yang melanggar ajaran. Tapi Umar tetap memberikan pertimbangan yang sangat manusiawi.
Banyak pemikiran segar Umar kemudian menjadi pegangan dalam pelaksanaan ibadah. Selain cerdas dan pemberani, Umar juga dikenal sangat kritis terhadap sabda-sabda Nabi. Termasuk tentang pelaksanaan shalat tarawih di musim Ramadhan. Terlepas dari soal perbedaan cara pandang tentang jumlah rakaatnya, hingga saat ini, masyarakat Muslim di dunia melaksanakan ibadah sunnah tarawih secara berjamaah. Selama bulan Ramadhan, masjid-masjid di Indonesia dipenuhi para jamaah ketika waktu isya tiba. Hikmah yang luar biasa, karena tidak seperti waktu-waktu shalat di luar bulan Ramadhan. Bahkan kondisinya seringkali melebihi kepadatan shalat jum’at.
Ramadhan memang sengaja datang untuk menebar hikmah kemanusiaan. Di tengah kekenyangan duniawi yang membuat kita lupa, ajaran ini mengajak kita menahan lapar dan dahaga, terutama untuk mempertajam kesadaran kolektif dengan sesama. Melatih manusia agar sanggup tenggelam dalam suasana kehidupan kaum dlu’afa. Mengetuk kesadaran spiritual untuk mengingatkan bahwa hidup ini tidak sendirian. Ibadah puasa sengaja mengajak kita memupuk kebersamaan sekaligus mewujudkan tuntutan ajaran tauhid sosial, membangun tatanan tauhidul ummah.
Lalu shahabat Umar menyerukan melaksanakan shalat sunnah tarawih berjamaah. Berkumpullah setiap individu yang menyatu dalam ikatan teologis untuk memupuk kebersamaan. Hanya satu bulan dari dua belas bulan yang setiap hari kita lalui. Selama bulan inilah kita hidupkan kembali semangat kemanusiaan yang berakar pada ajaran ukhuwah. Setiap diri kita merasakan suasana yang sama, sebagai simbol bahwa kebersamaan adalah tiang penting dari bangunan ukhuwah yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya.
Khalifah Umar telah merintis tradisi kebersamaan ini dengan menyatukan pelaksanaan shalat tarawih secara bersama. Suatu kreatifitas (tajdid) dalam ibadah dengan memberikan pertimbangan sosial untuk kemanusiaan. Sebab nilai kemanusiaan itu, salah satunya, terletak pada kesiapan individu untuk bersedia saling mengisi dan berbagi dengan sesama. Seperti itulah kebersamaan sesama manusia itu dibangun, berdiri bersama, ruku dan sujud bersama, berdo’a bersama, bahkan mengucapkan niat puasa pun bersama-sama. Di masjid setiap individu duduk bersama, dalam garis sejajar yang tidak memberikan kesempatan untuk meninggikan ataupun merendahkan antara satu dengan yang lainnya.
Sayangnya, dalam praktik i’tikaf, Umar saat itu tampaknya tidak sempat melakukan pembaruan. Karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan tradisi i’tikaf, diperlukan “Umar-umar bin Khattab” baru agar ajaran Islam tetap segar dan relevan dengan tuntutan sosial.
Taqarrub untuk Bangsa
Bangsa kita saat ini sedang terpuruk. Dibanding bangsa-bangsa lain di dunia, produktivitasnya sangat rendah. Kajian International Management Development (IMD) World Competitiveness Year Book 2005, menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-59 dari 60 negara yang dijadikan sampel studi (Soeroso Dasar, 2007). Jauh di bawah Thailand, Malaysia, Korea, China, India, dan Filipina. Data yang mengejutkan, sekaligus sangat memprihatinkan. Sebuah negara yang sangat kaya, tapi bisa menderita seperti ini.
Padahal, di tengah keterpurukan itu, sejumlah pengamat melihat saat ini tengah terjadi peningkatan gairah beragama masyarakat Indonesia yang menakjubkan. Selama bulan Ramadhan, syi’arnya gempita di mana-mana. Masjid-masjid dipenuhi jamaah. Setiap orang berlomba memanfaatkannya untuk memperoleh hikmah spiritual yang lebih besar. Ramadhan memang merupakan bulan yang sarat hikmah. Di rumah, frekuensi makan bersama dengan keluarga meningkat dibanding hari-hari di luar Ramadhan; di berbagai tempat pelayanan publik, di kantor-kantor, di hotel, dan di tempat-tempat kerja lainnya, tersedia banyak kesempatan untuk berkumpul di antara sesama pelaku ibadah puasa: buka puasa bersama, pengajian bersama, serta bentuk-bentuk silaturahmi lainnya. Kebersamaan semakin terasa di tengah kesibukan yang seringkali makin menjauhkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan.
Dua kenyataan yang sangat bertentangan. Seolah-olah telah terjadi pengaruh negatif secara signifikan antara pelaksanaan ajaran agama di satu sisi dengan semakin rendahnya produktivitas di sisi lain. Padahal seperti diisyaratkan oleh prinsip-prinsip ajaran, tidak seharusnya demikian. Jika Islam menghendaki pemeluknya senantiasa beribadah kepada Allah dan sangat menghargai, memuji, dan mengangkat derajat orang-orang yang bekerja, maka seharusnya seorang pemeluk Islam yang taat adalah mereka yang dekat dengan Allah dengan tetap memelihara produktivitas.
Adanya kenyataan sebaliknya, dimungkinkan karena telah terjadi pengamalan yang kurang tepat, yang salah satunya diakibatkan oleh kakunya pemaknaan terhadap sesuatu ajaran.
Jadi, gairah ummat dalam melaksanakan i’tikaf, sejatinya juga ditunjukkan oleh tetap produktivnya dalam memenuhi hajat kehidupan. Puasa tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk menjadi tidak produktif. I’tikaf juga tidak menjadi penghalang untuk meninggalkan fisik masjid dengan tetap memelihara spirit yang terkandung di dalamnya. Bekerja bukan berarti tidak bisa taqarrub; dan bertaqarrub tidak berarti harus meninggalkan kerja.